Lebih Banyak Tentara Dikirim ke Aceh dan Papua – ‘Saya Khawatir Trauma Konflik Kembali Muncul’
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin (24/11) menyatakan rencana penambahan pasukan militer di tiga kota strategis yang disebutnya sebagai center of gravity. Ketiga wilayah tersebut adalah Jakarta, Aceh, dan Papua.
Sjafrie belum memberikan rincian tambahan personel yang akan dikerahkan ke masing-masing daerah, namun ia menegaskan bahwa keputusan ini dilakukan dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar pembangunan bisa berjalan aman dan lancar. Sejawat Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer itu juga menyebut bahwa pemerintah akan membangun 150 batalion infanteri teritorial setiap tahunnya.
BBC News Indonesia melakukan wawancara dengan sejumlah warga di Papua dan Aceh untuk mengetahui pendapat mereka terkait rencana penambahan tentara di daerah mereka. Mereka sepakat bahwa penambahan tentara tidak dibutuhkan, dan menilai kebijakan ini berpotensi memicu trauma masa lalu. Kedua warga tersebut memiliki rekam jejak interaksi panjang dengan militer.
“Yang ada, saya khawatir trauma konflik akan muncul kembali,” kata Junaidi, salah seorang warga Aceh Timur yang pernah mengalami penerapan DOM dan darurat militer di Aceh.
Sementara pengamat menilai penambahan personel militer ini akan memperkuat “remiliterisasi” di segenap sendi kehidupan di Indonesia. BBC News Indonesia telah menghubungi Kementerian Pertahanan untuk mengonfirmasi kekhawatiran warga, tapi tidak mendapatkan jawaban.

Bagaimana tanggapan masyarakat Papua?
Rencana penambahan tentara di tiga daerah disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin usai rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (24/11). Alasannya, ketiga wilayah itu dinilai strategis bagi stabilitas keamanan negara. Jakarta dipilih karena statusnya sebagai pusat pemerintahan yang keamanannya harus dijamin.
“Kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” ujar Sjafrie di kompleks parlemen Jakarta. Sementara Aceh dan Papua dipilih karena merupakan gerbang negara, masing-masing di barat dan timur.
Kami mewawancarai beberapa warga di dua wilayah tersebut, mengingat keduanya memiliki rekam jejak interaksi panjang dengan tentara. Pemerintah pernah menerapkan DOM dan darurat militer di Aceh—di pengujung era Presiden Suharto sampai awal reformasi, sementara kehidupan warga Papua sampai saat ini masih lekat dengan tentara.
Benus Murip, seorang warga Lanny Jaya di Provinsi Papua Pegunungan berpendapat, kehadiran personel TNI—dan juga Polri—selama ini telah membuat warga di daerahnya tidak hidup tenang. Benus mencontohkan langkah pihak militer yang disebutnya kerap datang dan membangun pos keamanan tanpa berkoordinasi dengan masyarakat lokal. Tak jarang, tanah yang dibangun pos merupakan tanah milik masyarakat adat atau fasilitas publik.
“Mereka [TNI] tidak pernah tanya, langsung datang, mengambil tempat di mana ada pembangunan atau di mana ada kantor distrik, gedung sekolah,” ujar Benus. “Mereka sudah melakukan pendudukan, tanpa ada koordinasi. Saya melihat, mereka sudah jelas-jelas melakukan perampasan tanah atas masyarakat adat.”
Sampai saat ini, Benus mencatat setidaknya sudah ada delapan pos keamanan yang dibangun TNI di Lanny Jaya. Pada mulanya, terang Benus, pos-pos tersebut berdiri di wilayah perbukitan atau hutan, tapi belakangan merangsek ke pemukiman warga.

Selain itu, para tentara disebut Benus juga kerap meminta warga untuk mencarikan kayu bakar atau mengangkat barang milik TNI. Warga terpaksa mengikuti keinginan itu lantaran takut membantah, terang Benus. “Itu biasa terjadi dan saya melihat itu menimulkan kegelisahan. Mereka [mengikuti] bukan karena ikhlas, tapi karena keterpaksaan. Karena takut,” ujarnya.
Belum lagi beragam larangan aktivitas terhadap warga, seperti larangan berburu di hutan dan pembatasan jam kegiatan, hanya antara jam 6 pagi hingga 2 siang. Padahal, kata Benus, warga di Lanny Jaya selama bertahun-tahun kerap berburu di hutan pada malam hari. “Sejak TNI di sana, aktivitas itu disetop,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa aparat membatasi aktivitas berkebun maksimal 3 sampai 4 orang.
Benus mengaku sempat menyuarakan keluhan ini ke pimpinan militer setempat, tapi dijawab bahwa ihwal itu telah dikoordinasikan dengan pimpinan gereja. “Mereka sampaikan bahwa apa yang mereka lakukan, tindakan itu, bukan semena-mena, tapi sudah koordinasi dengan pimpinan gereja,” kata Benus. “Tapi pimpinan gereja itu mengiakan hanya karena takut, diintimidasi, dan lain-lain.”

Dalam sejumlah kesempatan, pemerintah berdalih penempatan tentara di sejumlah titik di Papua untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi warga dari gangguan milisi pro-kemerdekaan. Hal itu juga ditegaskan Sjarie dalam pernyataan di DPR. Namun, Benus mengatakan hal sebaliknya. “Pada dasarnya, masyarakat di sini tidak membutuhkan mereka. TNI justru datang membawa masalah baru, membawa penderitaan bagi orang asli Papua, khususnya di Lanny jaya,” ujarnya.
Senada pernyataan sejumlah perempuan Papua kepada BBC News Indonesia yang mengakui kehadiran TNI justru membuat masyarakat “secara psikologis tidak tenang.”

Salah seorang perempuan Papua yang meminta diidentifikasi sebagai Daby menilai, penambahan tentara justru berpotensi membuat masyarakat Papua kian tertekan. Selama ini, masyarakat sudah tertekan karena diliputi perasaan saling curiga, takut dianggap memihak kubu tertentu—TNI atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). “Di sini, warga itu saling tak percaya. Ketika ada sesuatu, takut dianggap berpihak dan dukung suatu pihak,” kata Daby. “Ruang gerak kami menjadi lebih sempit karena khawatir dan takut.”
Daby menyebut, militer selama ini memang kerap memberi bantuan kepada warga lokal. Namun, Daby menilai hal itu sebatas upaya membangun imaji positif, tapi tak menyentuh akar masalah dan keinginan warga Papua. “Mereka menutupi persoalan dengan kasih bantuan atau mengajar di sekolah, seolah baik-baik saja, tapi kami melihat itu hanya pencitraan,” ujar Daby.

Perempuan menjadi korban
Aktivis perempuan Papua bernama Ice Murip menambahkan, perempuan Papua adalah pihak yang sangat dirugikan dengan kehadiran tentara. Kerugian pertama, terang Ice, adalah potensi menjadi korban kekerasan seksual. “Kalau ditambah, potensi peningkatan kekerasan sangat mungkin terjadi,” ujar Ice.
Kerugian kedua, menurutnya, adalah fenomena para perempuan yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga akibat suami tewas dalam operasi keamanan militer. Fenomena ini, terang Ice, banyak terjadi pada pengungsi perempuan dari Lanny Jaya, Intan Jaya, atau Maybrat. “Akibatnya, banyak anak-anak yang kemudian tak bisa dapat pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi,” ujar Ice.

Pernyataan Ice sejalan dengan temuan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang dilansir pada 30 Agustus 2024. Dalam laporan berjudul Perempuan Papua Melawan Kekerasan yang Dilanggengkan Negara tersebut, INFID mendalami tiga fase operasi militer yakni periode 1977-1978, operasi militer 2005, dan pengejaran OPM 2007.
INFID menyatakan banyak perempuan Papua kala itu kehilangan ayah, paman, dan saudara laki-lakinya akibat operasi militer. Sementara para lelaki muda kemudian memilih meninggalkan kampung karena enggan terseret dalam operasi militer. “Sehingga mayoritas kampung dihuni janda dan anak-anak. Perempuan kemudian hidup dalam situasi miskin dan terisolasi dari wilayah sekitarnya,” tulis INFID dalam pemaparannya.
Lantas, apa harapan para perempuan Papua itu? Ice dan Daby bersepakat pada dua hal: batalkan penambahan tentara dan tarik personel yang telah ada di Papua. “Kehadiran tentara justru membuat warga tidak aman. Kehadiran mereka secara psikologis membuat warga tidak tenang… Rencana penambahan itu tidak dibutuhkan,” ujar Daby. Sementara Ice menyebut, “Kalau negara demokrasi, pihak yang berkonflik itu duduk bersama untuk mencari solusi permanen. Tapi, tarik dulu semua militer di Papua.”

“Saya khawatir trauma konflik itu muncul kembali,” Tak berbeda dengan warga Papua, sebagian warga Aceh juga mempertanyakan rencana penambahan personel di daerahnya. Seorang warga Aceh Timur yang sempat melalui DOM dan darurat militer mengaku khawatir dengan rencana penambahan tentara di wilayahnya. Ia meminta untuk diidentifikasi sebagai Junaidi.
“Saya khawatir trauma konflik itu muncul kembali,” ujar Junaidi. Pria 44 tahun sempat mengalami masa DOM dan darurat militer, yang digambarkannya “sangat traumatis.” Junaidi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama sempat menyaksikan mayat warga sipil di pinggir jalan. Badannya penuh luka, hasil penyiksaan. Insiden itu membuat ia dan keluarganya, serta warga Aceh Timur lain takut untuk keluar rumah. Mereka tak mau dicurigai tentara sebagai bagian kelompok separatis. Trauma itu pun terus dibawa sampai saat ini.
Jika sedang berada di tempat makan dan mendapati tentara atau polisi bersenjata, ia mengaku memilih kabur dan mencari tempat lain. “Badan saya menolak, enggak bisa. Sampai sekarang saya juga enggak bisa berkawan akrab dengan yang berbau militer,” ujarnya.

Saat DOM diberlakukan, Junaidi menyebut jumlah tentara di kampungnya sangat banyak dan rutin berkeliling. Mereka bersenjara lengkap dan tak jarang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang dicurigai bagian kelompok separatis. Alhasil, ia mengaku khawatir trauma kolektif itu akan kembali muncul jika pemerintah benar-benar menambah militer di Aceh. “Memang tidak otomatis kekerasan akan kembali terjadi, tapi soal trauma masa lalu itu saya khawatir dapat muncul lagi,” ujar Junaidi. Ia meminta pemerintah meninjau ulang rencana penambahan tentara di Aceh. “Yang harus dilakukan di Aceh saat ini bukan menambah tentara, tapi bagaimana masyarakatnya sejahtera,” kata Junaidi. “Lagipula, siapa yang mau dihadapi tentara di sini [Aceh]?”

Sepanjang penerapan DOM dan darurat militer, sejumlah pelanggaran HAM sempat terjadi. Berdasarkan catatan Komnas HAM, terdapat insiden Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Pidie (1989-1998), pembunuhan massal Simpang KKA di Aceh Utara (1999), dan pembunuhan Bumi Flora di Aceh Timur (2001). Adapula penghilangan paksa di Bener Meriah (2001) dan pembantaian massal di Jambo Keupok (2003). Semua kasus itu telah ditetapkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat, kecuali pembunhan Bumi Flora.

TNI juga akan dikerahkan jaga kilang minyak
Selain menambah batalion, Menhan Sjafrie juga menyebut pembangunan batalion untuk mengamankan industri strategis yang dianggap berkaitan dengan kedaulatan negara. “Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina. Ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” ujar Sjafrie. Apakah akan membuat bisnis militer kian kuat dan mengakar? Made tak bisa memastikan, dengan mengatakan, “Apakah mereka akan memperkaya diri, belum bisa dipastikan.”
Lalu, apakah rangkaian kebijakan ini buah dari revisi UU TNI yang disahkan DPR beberapa waktu lalu? Made menyangkal korelasinya. Ia menilai bahwa rangkaian kebijakan ini tak lebih dari diskresi Presiden Prabowo Subianto yang juga berlatar belakang militer. “Penambahan UU TNI itu kan cuma di ruang kecil. Ini diskresi saja,” kata Made.










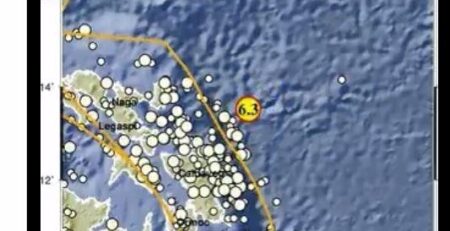

Tinggalkan Balasan